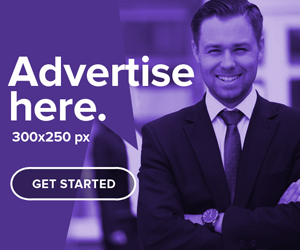Keberadaan pasar-pasar loak di suatu kota merupakan bagian dari budaya kota tersebut. Dari setiap jenis benda-benda yang diloakkan itulah dapat dibaca (meminjam istilah Afrizal Malna) “biografi” masing-masing benda tersebut. Karena itu, rencana pemindahan lokasi (relokasi) sejumlah pasar loak di Surabaya ke Bangkalan berarti mencabut identitas budaya kota (Surabaya) yang sebetulnya juga merupakan asset wisata potensial. Pemkot Surabaya nampaknya hanya mau cari gampangnya saja. Ibarat kata pepatah, buruk muka cermin dibelah.
Sekadar mengingatkan, bahwa keberadaan pasar-pasar loak di berbagai kota Indonesia sudah menjadi obyek wisata yang cukup dikenal. Sebut saja nama Jalan Surabaya di Jakarta, maka orang langsung tahu bahwa di sepanjang jalan itu dijual berbagai barang antik alias benda loak juga. Sementara di Surabaya, diam-diam sudah ada pedagang barang antik di sudut jalan dekat Gelora Pancasila. Nama Jalan Semarang di Surabaya juga sudah identik dengan pasar loak buku-buku bekas, sebagaimana Pasar Senen di Jakarta. Sementara barang-barang loakan lainnya juga sudah melekat dengan nama Jalan Kapasari, Gembong dan tentunya Pasar Loak Jalan Dupak. Identitas lokal seperti ini harus dipertahankan dan dikelola sedemikian rupa sebagai aset wisata dan budaya, bukan lantas dihapus begitu saja. Asal tahu saja, justru trend pasar loak ini belakangan sedang digemari, namanya Floah Market (?) yang konsumennya kalangan menengah ke atas.
Disebut Pasar Loak, karena biasanya memang menyediakan barang-barang bekas pakai dari hasil rombengan yang didapat dari tukang rombeng keliling. Cobalah perhatikan para pedagang loak di Jalan Kapasari dan Gembong. Hampir segala jenis barang ada di sana, mulai dari pakaian, alat-alat dapur, pertukangan, onderdil kendaraan, sampai dengan alat-alat elektronik seperti televisi dan komputer, yang entah dengan cara apa bisa mempercayai mampu berfungsi dengan baik (karena tak bisa dicoba, tidak ada aliran listrik).
Kawasan pasar loak ini semakin ramai pada hari Minggu karena (konon) semua tukang rombeng se-Surabaya tumplek bleg di sini. Boleh jadi Jalan Kapasari dan Gembong ini merupakan rendezvouz para tukang rombeng. Tentu saja, jalanan menjadi macet, karena tak ada pengaturan parkir. Suasananya semrawut, karena memang tidak ada penataan. Berulangkali pemkot berusaha menertibkan, namun selalu gagal dan kembali lagi ke kondisi semula yang centang perenang. Pernah ada niatan untuk menggusur, namun selalu saja ada yang membela dan menentangnya. Termasuk, menjelang Pemilu, ada spanduk besar warna merah bergambar partai tertentu bertuliskan: “Penggusuran No, Penertiban Yes.”
Begitulah, yang kemudian terjadi hingga sekarang, tidak digusur tapi juga tidak ditertibkan. Kawasan pasar loak ini seolah-olah hanya menjadi komoditas politik para penguasa, hanya menjadi sapi perahan bagi oknum-oknum petugas, dan diam-diam sebetulnya telah menjadi obyek wisata yang mengasyikkan. Bagi yang pernah ke pasar loak di Kapasari dan Gembong ini, ada keasyikan tersendiri jalan-jalan di sini. Rasanya tak cukup waktu sehari untuk berburu barang-barang yang “aneh”. Barang yang sebetulnya biasa, namun tanpa disangka-sangka tahu-tahu ditemukan di sana.
Meski disebut Pasar Loak, dalam prakteknya memang bukan hanya barang bekas yang dijual. Banyak juga barang baru, bukan bekas pakai, atau kelihatan seperti barang baru, dengan harga yang bisa jadi lebih mahal ketimbang barang baru di toko. Tidak terkecuali, barang-barang bajakan sangat mungkin juga beredar di sini. Tergantung konsumen sendiri, apakah mereka siap dengan kondisi seperti itu. Kalau kemudian tertipu dengan kualitas barang, itu sudah biasa. Pihak pedagang sendiri juga bisa “tertipu” karena telah menjual barang bagus dan langka dengan harga yang murah.
Cermin Dibelah
Rencana relokasi ini sebetulnya membuktikan ketidak-mampuan pemkot mengelola eksistensi dan pertumbuhan pasar loak yang identik dengan sektor informal. Seperti kata pepatah, buruk muka cermin dibelah. Apakah ini membuktikan bahwa pemkot memang sudah putus asa (dan menyerah) mengelola sektor informal? Bukankah sekarang sudah ada (sub) Dinas baru yang menangani sektor informal? Meskipun, tentu saja mengurusi para pedagang yang cenderung “rewel” dan “sulit ditertibkan” itu tidak bernilai populis dan politis.
Yang jelas, pemindahan dan pengumpulan pasar loak ke satu lokasi, tidak menjamin bahwa di lokasi lama bakal tumbuh pasar informal yang baru, karena karakter sektor informal bagaikan semut-semut yang cenderung merubung gula. Bahwa menata sektor informal tidak bisa menggunakan logika penataan sektor formal. Dan pemkot seharusnya tahu persis tentang hal ini. Disamping itu, pasar loak biasanya tumbuh di kota besar, sehingga memaksakan pasar loak di Bangkalan menjadi tidak alami dan tidak wajar.
Sangat tidak logis membayangkan bahwa pembeli (dari Surabaya) akan berbondong-bondong datang ke Bangkalan hanya sekadar mencari barang bekas di pasar loak. Bagaimana mungkin, misalnya, mereka yang biasanya membeli baju atau jaket bekas di Jalan Patua harus menyeberang ke Madura. Justru karena dijual di pasar loak itulah maka barang-barang yang tersedia biasanya memang konsumsi masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka tidak mungkin harus keluar ongkos transportasi lagi hanya untuk mencari sesuatu ke pasar loak yang jauh tempatnya. Hanya sebagian kecil barang loakan yang dibutuhkan masyarakat menengah ke atas, seperti barang-barang antik misalnya.
Optimisme Bupati Bangkalan yang mengaku bersedia merayu pedagang pasar loak di Surabaya untuk mau pindah ke Bangkalan patut diragukan hasilnya. Sangat mengherankan, apakah Bupati Fuad Amien Imron lupa dengan karakter warga Madura yang lebih suka bekerja di luar daerahnya? Perilaku merantau ini merupakan karakter budaya suatu etnis tertentu, bukan semata-mata soal ekonomi. Dan bukan zamannya lagi mengukur keberhasilan pembangunan (hanya) dari kacamata ekonomi.
Bisa saja pemkot Surabaya mengantisipasi tumbuhnya usaha baru di tempat yang lama, yakni dengan jalan mengalihfungsikan tempat itu menjadi pasar modern (plaza, ruko, kompleks bisnis dan semacamnya). Dan ini berarti, kalau sudah diniati sejak awal, ternyata pemkot memang punya skenario menggusur rakyat kecil. Bahwa pemkot memang lebih berpihak pada pengusaha ekonomi kuat. Bahwa pemkot memang tidak memiliki empati terhadap kesengsaraan rakyat yang semakin sulit mencari sesuap nasi seperti sekarang ini.
Mengaitkan rencana relokasi pasar loak ke Bangkalan dengan pembangunan jembatan Suramadu adalah hal yang mengada-ada belaka. Kemudahan akses transportasi dengan adanya jembatan Suramadu bukan alasan yang kuat. Kalau mau membangun pasar loak di Bangkalan ya bangun saja tanpa harus melakukan relokasi pasar loak dari Surabaya. Apalagi, katanya, Bupati Bangkalan mengaku siap dengan lahannya. Bangun saja pasar loak di Bangkalan sebagai daya tarik wisata, yang menyediakan barang-barang khas Madura yang sudah terkenal itu, dan pasti banyak peminatnya. Biarkan saja proses alami tumbuh secara wajar. Pedagang loak yang mau pindah ke sana yang silakan, yang bertahan di Surabaya ya biarkan saja, dan kalau toh ternyata lebih banyak diisi oleh pendatang baru, berarti hal itu sudah memperluas lapangan kerja.
Sekadar mengingatkan, bahwa keberadaan pasar-pasar loak di berbagai kota Indonesia sudah menjadi obyek wisata yang cukup dikenal. Sebut saja nama Jalan Surabaya di Jakarta, maka orang langsung tahu bahwa di sepanjang jalan itu dijual berbagai barang antik alias benda loak juga. Sementara di Surabaya, diam-diam sudah ada pedagang barang antik di sudut jalan dekat Gelora Pancasila. Nama Jalan Semarang di Surabaya juga sudah identik dengan pasar loak buku-buku bekas, sebagaimana Pasar Senen di Jakarta. Sementara barang-barang loakan lainnya juga sudah melekat dengan nama Jalan Kapasari, Gembong dan tentunya Pasar Loak Jalan Dupak. Identitas lokal seperti ini harus dipertahankan dan dikelola sedemikian rupa sebagai aset wisata dan budaya, bukan lantas dihapus begitu saja. Asal tahu saja, justru trend pasar loak ini belakangan sedang digemari, namanya Floah Market (?) yang konsumennya kalangan menengah ke atas.
Disebut Pasar Loak, karena biasanya memang menyediakan barang-barang bekas pakai dari hasil rombengan yang didapat dari tukang rombeng keliling. Cobalah perhatikan para pedagang loak di Jalan Kapasari dan Gembong. Hampir segala jenis barang ada di sana, mulai dari pakaian, alat-alat dapur, pertukangan, onderdil kendaraan, sampai dengan alat-alat elektronik seperti televisi dan komputer, yang entah dengan cara apa bisa mempercayai mampu berfungsi dengan baik (karena tak bisa dicoba, tidak ada aliran listrik).
Kawasan pasar loak ini semakin ramai pada hari Minggu karena (konon) semua tukang rombeng se-Surabaya tumplek bleg di sini. Boleh jadi Jalan Kapasari dan Gembong ini merupakan rendezvouz para tukang rombeng. Tentu saja, jalanan menjadi macet, karena tak ada pengaturan parkir. Suasananya semrawut, karena memang tidak ada penataan. Berulangkali pemkot berusaha menertibkan, namun selalu gagal dan kembali lagi ke kondisi semula yang centang perenang. Pernah ada niatan untuk menggusur, namun selalu saja ada yang membela dan menentangnya. Termasuk, menjelang Pemilu, ada spanduk besar warna merah bergambar partai tertentu bertuliskan: “Penggusuran No, Penertiban Yes.”
Begitulah, yang kemudian terjadi hingga sekarang, tidak digusur tapi juga tidak ditertibkan. Kawasan pasar loak ini seolah-olah hanya menjadi komoditas politik para penguasa, hanya menjadi sapi perahan bagi oknum-oknum petugas, dan diam-diam sebetulnya telah menjadi obyek wisata yang mengasyikkan. Bagi yang pernah ke pasar loak di Kapasari dan Gembong ini, ada keasyikan tersendiri jalan-jalan di sini. Rasanya tak cukup waktu sehari untuk berburu barang-barang yang “aneh”. Barang yang sebetulnya biasa, namun tanpa disangka-sangka tahu-tahu ditemukan di sana.
Meski disebut Pasar Loak, dalam prakteknya memang bukan hanya barang bekas yang dijual. Banyak juga barang baru, bukan bekas pakai, atau kelihatan seperti barang baru, dengan harga yang bisa jadi lebih mahal ketimbang barang baru di toko. Tidak terkecuali, barang-barang bajakan sangat mungkin juga beredar di sini. Tergantung konsumen sendiri, apakah mereka siap dengan kondisi seperti itu. Kalau kemudian tertipu dengan kualitas barang, itu sudah biasa. Pihak pedagang sendiri juga bisa “tertipu” karena telah menjual barang bagus dan langka dengan harga yang murah.
Cermin Dibelah
Rencana relokasi ini sebetulnya membuktikan ketidak-mampuan pemkot mengelola eksistensi dan pertumbuhan pasar loak yang identik dengan sektor informal. Seperti kata pepatah, buruk muka cermin dibelah. Apakah ini membuktikan bahwa pemkot memang sudah putus asa (dan menyerah) mengelola sektor informal? Bukankah sekarang sudah ada (sub) Dinas baru yang menangani sektor informal? Meskipun, tentu saja mengurusi para pedagang yang cenderung “rewel” dan “sulit ditertibkan” itu tidak bernilai populis dan politis.
Yang jelas, pemindahan dan pengumpulan pasar loak ke satu lokasi, tidak menjamin bahwa di lokasi lama bakal tumbuh pasar informal yang baru, karena karakter sektor informal bagaikan semut-semut yang cenderung merubung gula. Bahwa menata sektor informal tidak bisa menggunakan logika penataan sektor formal. Dan pemkot seharusnya tahu persis tentang hal ini. Disamping itu, pasar loak biasanya tumbuh di kota besar, sehingga memaksakan pasar loak di Bangkalan menjadi tidak alami dan tidak wajar.
Sangat tidak logis membayangkan bahwa pembeli (dari Surabaya) akan berbondong-bondong datang ke Bangkalan hanya sekadar mencari barang bekas di pasar loak. Bagaimana mungkin, misalnya, mereka yang biasanya membeli baju atau jaket bekas di Jalan Patua harus menyeberang ke Madura. Justru karena dijual di pasar loak itulah maka barang-barang yang tersedia biasanya memang konsumsi masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka tidak mungkin harus keluar ongkos transportasi lagi hanya untuk mencari sesuatu ke pasar loak yang jauh tempatnya. Hanya sebagian kecil barang loakan yang dibutuhkan masyarakat menengah ke atas, seperti barang-barang antik misalnya.
Optimisme Bupati Bangkalan yang mengaku bersedia merayu pedagang pasar loak di Surabaya untuk mau pindah ke Bangkalan patut diragukan hasilnya. Sangat mengherankan, apakah Bupati Fuad Amien Imron lupa dengan karakter warga Madura yang lebih suka bekerja di luar daerahnya? Perilaku merantau ini merupakan karakter budaya suatu etnis tertentu, bukan semata-mata soal ekonomi. Dan bukan zamannya lagi mengukur keberhasilan pembangunan (hanya) dari kacamata ekonomi.
Bisa saja pemkot Surabaya mengantisipasi tumbuhnya usaha baru di tempat yang lama, yakni dengan jalan mengalihfungsikan tempat itu menjadi pasar modern (plaza, ruko, kompleks bisnis dan semacamnya). Dan ini berarti, kalau sudah diniati sejak awal, ternyata pemkot memang punya skenario menggusur rakyat kecil. Bahwa pemkot memang lebih berpihak pada pengusaha ekonomi kuat. Bahwa pemkot memang tidak memiliki empati terhadap kesengsaraan rakyat yang semakin sulit mencari sesuap nasi seperti sekarang ini.
Mengaitkan rencana relokasi pasar loak ke Bangkalan dengan pembangunan jembatan Suramadu adalah hal yang mengada-ada belaka. Kemudahan akses transportasi dengan adanya jembatan Suramadu bukan alasan yang kuat. Kalau mau membangun pasar loak di Bangkalan ya bangun saja tanpa harus melakukan relokasi pasar loak dari Surabaya. Apalagi, katanya, Bupati Bangkalan mengaku siap dengan lahannya. Bangun saja pasar loak di Bangkalan sebagai daya tarik wisata, yang menyediakan barang-barang khas Madura yang sudah terkenal itu, dan pasti banyak peminatnya. Biarkan saja proses alami tumbuh secara wajar. Pedagang loak yang mau pindah ke sana yang silakan, yang bertahan di Surabaya ya biarkan saja, dan kalau toh ternyata lebih banyak diisi oleh pendatang baru, berarti hal itu sudah memperluas lapangan kerja.
Keberadaan pasar-pasar loak di Surabaya selama ini seharusnya dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi obyek wisata, sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Bukan jamannya lagi mengkambinghitamkan pedagang sektor informal (termasuk pedagang pasar loak) sebagai biang kemacetan dan kesemrawutan. Apalagi, kalau kemudian relokasi itu dijalankan dengan pendekatan kekuasaan (dan kekerasan) sebagaimana yang biasa terjadi dalam era sebelum ini. (Henri Nurcahyo)